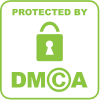Review Film: Blonde
Review Blonde: alur cerita, konflik, hingga lini masa dalam film ini tidak 100 persen mengikuti ataupun sesuai dengan kehidupan Marilyn Monroe.

Film memang tak melulu mesti menjadi produk hiburan. Terkadang, film juga menjadi gambaran ironi, kenyataan pahit, sekaligus tamparan keras akan kehidupan yang tak seindah khayalan. Blonde melakukan hal tersebut.
Meski berlabel film biografi, saya mungkin akan lebih setuju menyebut film yang dibintangi Ama de Armas ini sebagai film fiksi yang terinspirasi kejadian nyata, lebih tepatnya terinspirasi dari kehidupan sang ikon Marilyn Monroe.
Nama, karakter, latar dalam Blonde mungkin disesuaikan dengan data dan cerita soal kehidupan Marilyn Monroe. Namun sejatinya, alur cerita, konflik, hingga lini masa dalam film ini tidak 100 persen mengikuti ataupun sesuai dengan kejadian di dunia nyata.
Hal itu dulu yang saya ingin sampaikan di awal review Blonde ini, perspektif bahwasanya saya yakin film yang ditulis dan digarap oleh Andrew Dominik dari buku karangan Joyce Carol Oates ini akan lebih baik dipandang sebagai film fiksi alih-alih sebagai film biografi.
Blonde menggambarkan kondisi paling pahit yang bisa dialami seorang perempuan dalam industri hiburan, industri yang mengeruk keuntungan dengan menghibur penikmatnya dan mungkin saja berdiri di atas tangisan juga penderitaan pelakunya.
Kenyataan pahit itu terlihat dari bagaimana sosok Norma Jeane alias Marilyn Monroe (Ana de Armas) dipandang dan diperlakukan dalam industri hiburan Hollywood yang seksis, terlalu maskulin, dan jelas merendahkan perempuan.
 Review Blonde: alur cerita, konflik, hingga lini masa dalam film ini tidak 100 persen mengikuti ataupun sesuai dengan kehidupan Marilyn Monroe. (dok. Netflix) Review Blonde: alur cerita, konflik, hingga lini masa dalam film ini tidak 100 persen mengikuti ataupun sesuai dengan kehidupan Marilyn Monroe. (dok. Netflix) |
Sejumlah asumsi itu juga sebenarnya tak sepenuhnya karangan pengarang. Masih jelas dalam ingatan berbagai skandal pelecehan dan ketimpangan berbasis gender yang terjadi di industri hiburan, baik di Hollywood maupun di Indonesia.
Memang, Blonde dengan segala penggambaran dalam film ini secara brutal menonjolkan seksisme, dramatisasi yang cukup berlebihan, hingga kekerasan yang bisa saja terjadi pada siapa pun, bukan cuma perempuan.
Namun apakah itu menjadi dasar film ini patut dicela seperti yang ramai belakangan ini? Saya rasa hal itu mungkin karena publik terbiasa atau rindu akan film yang menampilkan angan, harapan, atau inspirasi atas sesuatu karena dunia nyata begitu sulit untuk diterima.
Hal itu persis seperti yang jadi tujuan dari jualan Hollywood: American Dream, bahwasanya segala sesuatu yang diinginkan bisa terwujud bila kita berusaha dan terus bermimpi. Akan tetapi, seringkali terlupa bahwa kehidupan ini berjalan tidak atas kehendak manusia.
Mimpi dan angan-angan itu seringkali membutakan orang bahwa jalan terjal yang dilalui bukan hanya karena sekadar rintangan, tetapi memang kondisi pahit dari apa yang ingin diperjuangkan.
Blonde menampilkan gambaran ketika industri media dijalankan juga dikuasai oleh para laki-laki seksis yang hanya berorientasi pada cuan, cuan, dan cuan.
 Review Blonde: film ini menampilkan gambaran ketika industri media dijalankan juga dikuasai oleh para laki-laki seksis yang hanya berorientasi pada cuan, cuan, dan cuan. (dok. Netflix) Review Blonde: film ini menampilkan gambaran ketika industri media dijalankan juga dikuasai oleh para laki-laki seksis yang hanya berorientasi pada cuan, cuan, dan cuan. (dok. Netflix) |
Hal itu belum termasuk dari konotasi "hiburan" yang menarik bagi publik adalah pada topik dan objek yang banyak berkaitan dengan selangkangan, yang memuaskan gairah juga fantasi. Apakah gambaran ini terasa asing pada saat ini? Saya rasa tidak juga.
Blonde menggambarkan hal pahit di balik mimpi indah yang membutakan akal, meskipun disajikan dengan cara yang sangat tidak nyaman dan justru bikin sering-sering mengelus dada.
Lanjut ke sebelah...

 oujisama
oujisama