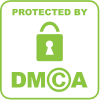Review Film: The Exorcist: Believer
Review film: The Exorcist Believer susah payah mempertahankan 'nyawa' The Exorcist yang legendaris di tengah selera horor yang sudah berubah.

Lebih dari 50 tahun lalu, William Peter Blatty pernah menulis dalam novelnya yang kemudian terkenal dan mengantarkan dia mendapatkan Piala Oscar pada 1974, The Exorcist, pada Bab III bagian 2:
Mendadak lengan Karras yang merinding bukan lagi disebabkan oleh udara kamar yang sedingin es, melainkan oleh apa yang dilihatnya di dada Regan; oleh tulisan-timbul yang membentuk huruf-huruf tegas dari kulit yang menonjol dan berwarna merah darah. Dua kata:
tolong aku
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(The Exorcist, cetakan September 2013, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ingrid Nimpoeno dan diterbitkan oleh Serambi).
Saya masih ingat gambaran penderitaan si bocah Regan dalam novel dan film The Exorcist (1973) akibat kerasukan. Kisah karangan Blatty yang terinspirasi dari kisah nyata pada akhir dekade '40-an di Amerika Serikat itu pun menjadi tonggak sejarah baru bagi perfilman horor.
Dalam The Exorcist, Blatty tidak menjadikan sikap aneh dan 'ajaib' yang berada di sekitar manusia yang dikuasai iblis sebagai sajian utama. Blatty menampilkan horor yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia: menghadapi hal di luar kesanggupannya.
Berbagai gejolak emosi manusia ada dalam kisah yang konfliknya sebagian besar berada di kamar Regan itu, keangkuhan, keputusasaan, ketakutan, kemarahan, hingga bertahan dalam sedikit harapan.
Hal itulah yang bagi saya menjadi alasan mengapa The Exorcist menjadi karya tulis dan film horor legendaris --dan mungkin saja-- jadi penyebab mendapatkan nominasi Best Picture Academy Awards ke-46 pada April 1974.
Hingga ketika kelanjutan kisahnya, setelah sekian puluh tahun berlalu, muncul dalam The Exorcist: Believer (2023), membuat saya bersemangat. Sejak awal, saya sebenarnya tak mau berharap banyak dengan film garapan David Gordon Green dan naskahnya dibantu Peter Sattler ini.
Pertama, sang kreator asli yakni William Peter Blatty jelas tak terlibat mengingat ia sudah meninggal pada 2017. Namun nyatanya juga tidak ada keturunannya yang terlibat dalam penggarapan film ini.
 Kreator asli The Exorcist, William Peter Blatty. Review film The Exorcist Believer: saat rampung melihat film ini, hasilnya tidak kecewa-kecewa amat. (Dok. Wikimedia/CC BY-SA 3.0) Kreator asli The Exorcist, William Peter Blatty. Review film The Exorcist Believer: saat rampung melihat film ini, hasilnya tidak kecewa-kecewa amat. (Dok. Wikimedia/CC BY-SA 3.0) |
Kedua, pengalaman buruk dari kelanjutan-kelanjutan The Exorcist yang nyaris tak ada yang beres. Entah bagaimana, The Exorcist (1974) seolah menjadi film yang tak akan bisa ditandingi oleh penerusnya meski sudah menggunakan teknologi dan cara narasi yang lebih mutakhir.
Sehingga saat saya rampung melihat The Exorcist: Believer, saya harus akui tidak kecewa-kecewa amat. Naskah yang ditulis Green dan Sattler sebenarnya justru terasa agak lebih baik dibanding saga-saga film The Exorcist lainnya.
Narasi yang bertempo lambat dan kronologis jelas persis seperti film-film The Exorcist lainnya. Belum lagi titik berat yang berada di dalam keluarga yang menjadi ciri khas The Exorcist, yang kemudian diikuti banyak film horor setelahnya.
Namun titik krusialnya adalah bukan pada apakah si anak kerasukan bisa berjalan merangkak di dinding, atap, dan badannya menekuk terbalik sambil melayang di udara. Titik krusialnya adalah bagaimana The Exorcist: Believer menangkap horor dalam diri manusia dalam kemelut saat itu.
Saya harus mengatakan Green dan Sattler susah payah bisa menangkap roman gejolak tersebut tanpa harus mendramatisir berlebihan seperti film-film horor pop lainnya. Setidaknya, tak perlu ada tangis derai air mata berteriak-teriak, rambut ditarik makhluk tak kasat mata, hingga piring terbang ke sana ke mari.
Lanjut ke sebelah...
[Gambas:Video CNN]

 oujisama
oujisama