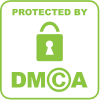Michelle Yeoh dan Persepsi Monolitik Asia
Karakter Indonesia sering diperankan aktor Amerika-Asia yang tak mirip kebanyakan orang Indonesia. Dunia, terutama Eropa dan Amerika, masih menganggap Asia sebuah monolit—selembar struktur raksasa tanpa aneka tekstur.

-
Minggu ini diawali dengan berita hangat untuk Asia, kemenangan Michelle Yeoh sebagai Pemeran Wanita Terbaik dalam film Everything Everywhere All at Once di perhelatan Academy Awards di Amerika Serikat. Filmnya pun menyabet penghargaan Film Terbaik. Yeoh adalah perempuan Asia pertama dan perempuan non-Kaukasia kedua yang memenangi penghargaan ini dalam 95 tahun sejarah Oscar. Butuh 74 tahun Oscar berjalan baru Pemeran Wanita Terbaik jatuh ke aktris berkulit berwarna, Halle Berry, dan butuh 21 tahun lagi sebelum aktris Asia meraihnya.
Apakah karena kualitas akting kulit berwarna berkualitas rendah? Sama sekali tidak. Banyak film bagus puluhan tahun terakhir ini yang dihasilkan industri perfilman Hong Kong, India, Indonesia, Meksiko, Spanyol, Turki, bahkan Iran. Dari Indonesia, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017) dinominasikan di Cannes Festival dan menang banyak penghargaan di Asia Pasifik.
Namun, harus diakui kekuatan budaya populer Amerika Serikat yang menjadikan Hollywood kiblat terkuat perfilman dunia membuat ketimpangan demografi anggota Academy Awards, padahal merekalah yang berhak memberikan suara. Seperti dilansir LA Times, bahkan setelah usaha pemerataan karena dikritik publik, pada tahun 2021 tetap hanya ada sepertiga wanita dan seperlima kulit berwarna dari 10.000 anggota Academy Awards yang keanggotaannya pun berdasarkan undangan. Pantas susah sekali bagi ”orang luar” Hollywood untuk menang.

Aktris Malaysia, Michelle Yeoh, membawa piala Oscar.
Saat naik layar tahun 2018, Crazy Rich Asians yang menggambarkan kehidupan jetset keturunan China di Singapura disambut hangat keturunan Asia di Amerika karena keluar dari stereotipe karakter Asia di layar; miskin, kutu buku, jago bela diri. Terakhir kali film top Hollywood sepenuhnya berbintangkan keturunan Asia adalah The Joy Luck Club (1993), juga diadaptasi dari buku, yang mengisahkan bentrok budaya para ibu imigran China dengan anak mereka yang besar sebagai warga Amerika.
Kemenangan komedi satir Parasite dari Korea Selatan sebagai film terbaik Oscar 2019 adalah tonggak besar ”pengakuan” terhadap sinematografi yang datang dari Asia. Bagi saya pribadi, lebih berarti lagi karena kategori filmnya yang kontemporer, bukan stereotipe Asia seperti bela diri (Crouching Tiger Hidden Dragon, 2000) atau budaya lawas (Memoirs of a Geisha, 2005). Siapa pun di dunia bisa menarik persamaan dengan pergulatan kelas yang disajikan brilian oleh sutradara Bong Joon-ho itu.
Mengapa tipe film Asia di panggung dunia berarti bagi saya? Karena saya sadar dunia, terutama Eropa dan Amerika, masih menganggap Asia sebuah monolit—selembar struktur raksasa tanpa aneka tekstur, rasa atau warna. Padahal, Asia bukan hanya warna kulit dan tipe wajahnya, melainkan juga kisahnya. Antara Asia Timur dan Selatan berbeda, di antara sesama Asia Tenggara bermacam, dan kesemua ini beda lagi dengan Turki yang terasimilasi ke Barat.
Contoh konkret, semua film di atas cukup berbeda dengan karya Asia lain seperti Monsoon Wedding (2001) dan The Namesake (2006), dua film pemenang penghargaan besutan Mira Nair, atau Slumdog Millionaire (2008). Bahkan, saat mengisahkan konflik klasik antara orangtua imigran dan anak yang dibesarkan di Amerika pun, baik The Joy Luck Club, The Namesake, maupun Everything Everywhere All at Once punya perspektif, penyampaian, dan pesan penutup yang tidak seragam.
Pukul-rata Hollywood terhadap narasi dan karakter Indonesia juga terjadi, bertahun-tahun dengan jengkel saya tandai. Karakter Indonesia sering diperankan aktor Amerika-Asia yang tak mirip kebanyakan orang Indonesia, mulai dari serial TV seperti Law & Order, JAG dan West Wing, sampai ke film layar lebar seperti Gold dan The Year of Living Dangerously. Dekor pun sering asal tempel, contohnya rumah bergapura Bali dengan jawara silat berbusana Betawi di The Accountant. Dialog bahasa Indonesia acap kaku, bak bahasa Inggris diterjemahkan mentah-mentah ke bahasa Indonesia. Belum lagi kebiasaan mengarang bebas (provinsi fiktif di Anaconda: The Blood Orchid) dan stereotipe negara rusuh atau sarang kriminal (The Sweetest Thing, The Devil’s Advocate, Blackhat). Ampun.
Tak heran saat Christine Hakim muncul dalam adegan pembuka episode kedua serial TV The Last of Us sebagai ilmuwan, se-Indonesia bersorak. Selain cerdas, karakternya penting dalam plot. Dialognya masuk akal, desain set dan pemilihan figuran relatif realistis. Walau hanya muncul 5-7 menit, kekuatan akting Christine mengguncang pemirsa di seluruh dunia, sebagian menganggapnya pantas dapat penghargaan hanya karena adegan itu. Dibandingkan dengan karakter yang ia perankan sebelumnya di Eat, Pray, Love sebagai wanita lokal tertindas yang ”diselamatkan” turis asing di Bali, karakter ini lebih bermakna.

-
Yeoh sendiri pernah mengeluhkan sempitnya pilihan peran untuk aktris dari Asia atau keturunan Amerika-Asia dalam forum diskusi dengan aktris Hollywood terkenal. Padahal, karena kefasihan bahasa Inggris-nya, Yeoh relatif banyak dapat kesempatan. Gong Li tidak bertahan lama di percaturan Hollywood, konon karena kendala bahasa. Yeoh dan Gong adalah produk industri perfilman Hong Kong yang begitu besar, tetap terantuk-antuk di Hollywood. Bollywood dari India yang bahkan pernah merajai bioskop Indonesia beberapa dekade lalu, dan tetap raksasa di Asia, belum terwakili lagi oleh aktor dan aktris muda setelah generasi Anil Kapoor, Ashwarya Rai, dan almarhum Irrfan Khan. Bayangkan perjuangan pelakon dari Indonesia.
Di mana peluang Indonesia? Saya merasa keberadaan teknologi streaming yang membuka banyak kanal tontonan via internet bisa jadi pintu masuk film yang berani, riil, dan tidak terkungkung stereotipe. Tapi, studio raksasa di Hollywood dan Eropa yang menguasai layar perak tetap perlu mengambil keputusan bisnis untuk memberikan porsi lebih banyak bagi berbagai naskah dan talenta Asia untuk memperkaya pilihan tontonan di benua mereka. Mimpi saya, sedekade lagi, saya tidak ditanya orang Eropa dan Amerika apa beda Indonesia dan Malaysia, di bagian sebelah mananya Bali terletak Indonesia, atau mengapa bahasa Indonesia berbeda dengan Thai dan Tagalog—karena akhirnya dunia terekspos pada tontonan dari Asia yang beragam. Yeoh yang keturunan China dari Malaysia berbeda dengan Gong yang berasal dari Hong Kong, dan mereka bukan Kris Aquino dari Filipina, apalagi Christine Hakim dari Indonesia. Asia memang bukan bukan monolit nan seragam.
Tan Sri Michelle Yeoh, tahniah dari Indonesia! Kami ikut bangga. Terima kasih sudah mendobrak pintu perfilman dunia untuk Asia.
Lynda Ibrahim
konsultan bisnis & penulis

 oujisama
oujisama