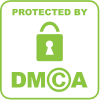Buruh Indonesia, Menolak Dibungkam Sejak Dulu Kala
Pemberontakan buruh di Indonesia punya sejarah panjang.


Kaum buruh alias kaum pekerja yang mendapatkan libur istimewa mereka 1 April ini sudah lama terjalin dalam sejarah bangsa. Keberadaan dan perlawanan kaum ini juga mewarnai jalan sejarah bangsa. Dalam sejarah modern, salah satu pemberontakan buruh paling fenomenal di Indonesia terjadi pada 1933 silam.
Saat itu, menurut wartawan Republika sepanjang zaman, Alwi Shahab, krisis ekonomi atau pada 1930-an, pengaruhnya sangat terasa di Hindia Belanda. Kala itu pemerintah kolonial menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17 persen sejak 1 Januari 1933.
Dimulai dengan kekacauan di Wall Street, salah satu pasar saham terbesar di dunia, yang telah membuat pincangnya neraca perdagangan dan dengan cepat meluncur berputar ke bawah. Pabrik-pabrik tutup dan beribu-beribu penganggur antri menanti pembagian ransum.
Sosialisme, komunisme, dan radikalisme marak mendapat dukungan sebagai reaksi terhadap krisis yang dinilai sebagai kegagalan kapitalisme itu. Dalam pemilu 1932 lebih dari satu juta orang Amerika memberikan suara untuk sosialisme atau komunisme.
Kelaparan dan kemiskinan membuat para petani AS berubah menjadi kaum radikal, karena hasil pertanian mereka tidak dapat menutupi biaya produksi. Mereka bersatu menolak membayar pajak dan memusnahkan surplus pertaniannya dengan membuangnya ke laut, sungai, bahkan selokan-selokan.
Depresi ekonomi di AS itu seperti layaknya penyakit menular dengan cepat menjalar ke seluruh dunia, karena AS menghentikan pinjaman untuk luar negeri dan menaikkan tarif sangat tinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Jerman juga bangkrut, dan rakyatnya berpaling kepada Adolf Hitler, dengan harapan pemimpin Nazi ini dapat menolong Jerman dari kehancuran. Inggris yang kala itu memiliki jajahan di empat benua terpaksa melepaskan cadangan emasnya.
Sedangkan Jepang yang masa itu sedang maju perindustriannya memanfaatkan dunia yang sedang sakit dengan menyerang Manchuria dan merampasnya dari Cina. Sampai kini, hubungan Jepang-Cina tidak harmonis, akibat ekspansi negeri sakura ke daratan Cina.
Dalam situasi ekonomi yang lesu itu, justru gerakan perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial makin menjadi-jadi. Pemerintah kolonial menangkap dan memenjarakan Sukarno dan kawan-kawannya yang radikal. Mereka dituduh menghasut rakyat supaya melawan kekuasaan Belanda.
Di saat-saat demikian itu Belanda makin kewalahan menghadapi perlawanan rakyat yang makin meningkat. Lebih-lebih pada pada 5 Februari 1933 ketika tiba-tiba terjadi pemberontakan di atas kapal angkatan laut Zeven Provincien (Kapal Tujuh Provinsi) milik Belanda.
Peristiwanya terjadi di lepas pantai Sumatera, tepatnya di Olele, dekat Kutaraja (kini Banda Aceh). Pemberontakan itu dilakukan sekitar pukul 20.00 malam, saat hampir separoh perwira kapal, termasuk komandannya, sedang pergi ke darat menghadiri pertemuan ramah tamah dan hiburan di Kutaraja.
Pengambilalihan kapal tempur Belanda itu dilakukan para marinir pribumi, yang tidak puas terhadap pemotongan gaji mereka. Inti pemberontak terdiri dari 10 pribumi, kemudian diikuti serentak oleh sekitar 180 lainnya.
Sebanyak 50 keturunan Eropa yang juga tidak puas, ikut bergabung dengan pemberontak. Yang lain menjauhkan diri atau mencoba menenangkan keadaan dengan melakukan perundingan bagi pemecahan damai, sementara para perwira masih ada di darat.
Dua jam setelah pengambilalihan, kapal dapat berlayar dikemudikan oleh marinir tingkat pertama Kawilarang. Kapal berlayar di sepanjang perairan Sumatra menuju Surabaya. Pada 6 Februari 1933 diumumkan lewat radio ke seluruh dunia bahwa pemberontakan dilakukan karena protes terhadap pemotongan gaji serta solidaritas terhadap para pemimpin buruh yang ditahan.
Ketika kapal berada di Selat Sunda, Gubernur Jenderal Des Jonge dan Markas AL Belanda memutuskan untuk menghentikan kapal tersebut dengan cara mencegatnya serta mengerahkan pesawat terbang. Pada 10 Februari 1933 setelah berlayar selama empat hari, posisi kapal dapat diketahui dari udara.
Sebuah bom dijatuhkan dari pesawat pengebom Dornier Wall. Bom yang meledak dekat jembatan kapal, mengakibatkan 19 orang gugur, 16 orang Indonesia, dan tiga Eropa. Pemberontakan yang sangat mengguncangkan itu, dan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, di luar perhitungan di Hindia maupun di Belanda, dengan cepat berakhir secara dramatis.
Dalam sidang Volksraad (Dewan Rakyat bentukan Belanda) ke-85 Komandan Angkutan Laut Belanda merangkap Kepala Departemen Marine di Hindia Belanda, JF Osten, melaporkan peristiwa pemberontakan tersebut.
Sementara itu, tokoh Betawi, MH Thamrin, yang jadi anggota Volksraad, dengan keras memprotes penangkapan terhadap para pejuang kemerdekaan, termasuk teman dekat Bung Karno. Thamrin juga protes keras ketika pemred Soeara Oemoem Surabaya, Taher Tjindarbumi, ditahan pemerintah kolonial karena tulisannya tentang Pemberontakan Kapal Tujuh dianggap merugikan Belanda. Dia mendekam di penjara Kalisosok selama 20 bulan.
Menurut Canderian Attahiyat dari Dinas Sejarah dan Kebudayaan DKI, para pengambil alih kapal milik AL Belanda itu ditawan sementara di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jakarta. Bahkan ada yang meninggal di pulau itu.
Buruh ideologis
Selepas kemerdekaan, aksi buruh berupa demo-demo telah dilakukan. Di masa demokrasi liberal (1950-1959) saat partai-partai politik yang jumlahnya puluhan, masing-masing mendirikan serikat-serikat buruh atau karyawan yang menjadi pendukung utamanya.
Di tiap partai serikat buruh cabang atau ranting, seperti serikat buruh perkebunan, serikat buruh angkutan, bioskop, dan banyak lagi. Waktu itu, saat partai politik yang banyak itu saling bersaing, aksi mogok merupakan modal mereka untuk menarik simpati massa rakyat.
Di masa itu, organisasi buruh yang memiliki massa besar adalah SOBSI (Sentral Organisasi Bujruh Seluruh Indonesia) sebuah organisasi buruh PKI. SOBSI yang paling kerap melakukan demo-demo. Lawan utama SOBSI adalah SBSI (Serikat Buruh Islam Indonesia) yang diketuai Jusuf Wibisono. Kedua organisasi ini, dalam membela nasib buruh, saling bertentangan. Tidak jarang tuntutan organisasi buruh yang satu ditentang organisasi buruh yang jadi lawan politiknya.
Di masa demokrasi liberal, partai-partai politik juga memiliki surat kabar yang menjadi corong partainya. Tidak seperti sekarang, masing-masing surat kabar saling seran. Kerap terjadi polemik, seperti yang terjadi antara surat kabar Merdeka pimpinan BM Diah dengan Harian Rakjat milik PKI.
Organisasi buruh yang memiliki massa cukup besar adalah Serikat Buruh Marhaen milik PNI yang aksi-aksinya selalu didukung koran Suluh Indonesia milik PNI. Sedangkan, NU memiliki ormas buruh yang kegiatannya selalu dimuat dalam surat kabar Duta Masyarakat. Jadi, ketika itu suara buruh terpecah sesuai ideologi partainya.
Setelah kembali ke UUD 1945 pada 1959, Indonesia memasuki demokrasi terpimpin. Sasaran demo ditujukan kepada antiimperialis yang sering dikumandangkan Bung Karno dalam pidato-pidatonya. Massa buruh ramai demo-demo di kedutaan asing yang mereka anggap sebagai nekolim (neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme), istilah yang berasal dari Bung Karno. Tapi, tidak berarti tidak ada perbedaan pendapat dalam masyarakat.
Saat memuncak pertentangan politik antara kelompok kiri dan penentangnya, terjadilah dua istilah yang saling berlawanan. Kelompok kiri menggunakan istilah buruh untuk para pekerja. Sedangkan, kelompok antikomunis menggunakan istilah karyawan.
Kelompok kiri yang dimotori oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), organisasi buruh PKI, menyerang keras. Mereka juga menganggap, karyawan yang tergabung dalam Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) sebagai lawan politiknya. Kalau SOBSI diketuai oleh Munir dari Komite Central PKI, SOKSI dipimpin oleh Suhardiman dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
Bagi SOBSI dan para pendukungnya, istilah karyawan tidak cocok menjadi sebutan untuk kelas pekerja dan dianggap sebagai sebutan kelompok imperialis. Menurut mereka, itu bukan mencerminkan kelas pekerja. Bahkan, SOBSI dan kelompok kiri menuduhnya sebagai kontrarevolusi (istilah yang ditakuti ketika itu).
Pertentangan antara kedua kelompok itu sangat tajam dan menjadi salah satu isu politik utama ketika itu. Bahkan, pertentangan ini terjadi di level atas, termasuk di antara pejabat-pejabat tinggi negara yang saat itu memang kerap saling beda pendapat.
Alwi Shahab alias Abah Alwi menuturkan, saat masih menjadi wartawan pemula di Kantor Berita Antara merasakan konfrontasi antara kedua kubu itu. Selain itu, di Antara juga terjadi pengelompokan dua kubu ini di tengah para pekerjanya, yaitu Serikat Buruh Pekabaran Antara (SBPA) dan dua kubu lainnya yang memakai istilah karyawan.
Yaitu, Ikatan Karyawan Antara (IKA) yang pengurusnya orang-orang Murba, dan IKRAR (Ikatan Karyawan Antara), yang anggota-anggotanya bekas wartawan PIA sebelum disatukan Bung Karno menjadi Antara.
Abah Alwi mengenang, bagaimana ketiganya saling rebutan agar para wartawan dan karyawan Antara menjadi anggotanya. Puncaknya terjadi ketika peristiwa G-30-S pada 30 September 1965.
“Sungguh menyedihkan, mereka yang menjadi SBPA dianggap sebagai kekuatan kiri meski hanya ikut-ikutan. Mereka ditangkap, dipenjara, dan di Pulau Buru-kan,” tulis Abah Alwi.
Waktu itu, seperti juga sekarang, kerap terjadi aksi-aksi kaum pekerja, terutama dari kelompok buruh. Mereka berunjuk rasa, baik terkait politik dan juga menuntut kenaikan upah serta penurunan harga akibat inflasi yang menggila ketika terjadi kenaikan dan hilangnya barang kebutuhan pokok dari pasar. Tapi, tidak sampai terjadi unjuk rasa buruh dengan ancaman-ancaman, termasuk sweeping terhadap pabrik-pabrik.
Tentu saja pada 1960-an, saat politik saling menerpa antara dua kekuatan yang berhadapan, Jakarta belum memiliki jalan tol. Jumlah mobil dan kendaraan bermotor belum seperti sekarang. Jadi, demo belum sampai mengganggu aktivitas para pekerja saat ke kantor dan ke tempat-tempat lain.
Adanya gerakan Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang ditentang keras kelompok kiri aksi buruh juga ikut terlibat antara yang pro dan kontra. Bahkan, ketika film-film Amerika dan Barat dilarang, serikat buruh bioskop menolak untuk memutar film-film tersebut.
Jadi, di masa ini aksi-aksi buruh bersama masyarakat lebih banyak soal politik. Lebih-lebih, saat konfrontasi dengan Malaysia, hampir tidak ada demo menuntut perbaikan nasib dan upah.
Pembunuhan di masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, serikat-serikat buruh yang banyak itu disatukan oleh Pak Harto. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik, mulailah massa ketika aksi-aksi buruh tidak dibenarkan. Pokoknya, suara buruh harus sejalan dengan pemerintah. Yang menjadi pimpinan organisasi buruh/karyawan adalah orang yang tidak diragukan lagi kesetiaannya terhadap Pemerintah Orde Baru.
Pada paruh akhir masa Orde Baru terjadi juga aliran investasi dan pendirian banyak pabrik di Indonesia. Hal ini memunculkan lahirnya massa buruh yang baru, banyak yang tak puas dengan standar upah kala itu. Dihimpit keadaan, para buruh mulai berani melakukan unjuk rasa.
Pada 4 Mei 1993, misalnya, terjadi keresahan di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik perakitan arloji di Porong, Sidoarjo, dengan pekerja sekitar 500-an orang.
Wartawan Republika Farid Gaban saat itu mencatat, para buruh mogok total, antara lain, menuntut kenaikan upah pokok dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 per hari; sebuah kenaikan upah kurang dari Rp 15 ribu per bulan. Di antara para buruh yang berunjuk rasa, ada seorang perempuan bernama Marsinah (24 tahun).
Meski menurut para buruh tuntutan itu sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang dikeluarkan setahun sebelumnya [No. 50/92], perusahaan tak memenuhinya. Dan pada 5 Mei, 13 buruh yang dianggap menghasut (Marsinah tak termasuk di dalamnya) digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo setelah sebelumnya Komando Resort Militer (Koramil) Porong tak mampu mengatasinya. Di Kodim, mereka dipaksa mundur dari pekerjaan.
Pada malam harinya, Marsinah menuju pabrik untuk menyampaikan surat kepada direksi, isinya mempertanyakan pemaksaan pengunduran diri 13 rekannya. Marsinah lenyap malam itu juga dan tak pernah pulang dalam keadaan hidup.
Marsinah ditemukan tergeletak tewas pada 9 Mei 1993 di sebuah pondok hutan jati beberapa kilometer dari desa asalnya di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dia menghilang empat hari sebelumnya di Sidoarjo, tempatnya bekerja, sekitar 200 kilometer dari jasadnya ditemukan.
Gadis pekerja itu tak hanya tewas. Dia dibunuh secara brutal, diperkosa, dan dianiaya. Kematian Marsinah kala itu memicu kemarahan kaum buruh Indonesia dan internasional. Kejadian itu ikut mendorong para buruh memprotes keras Orde Baru yang runtuh lima tahun kemudian.

 oujisama
oujisama